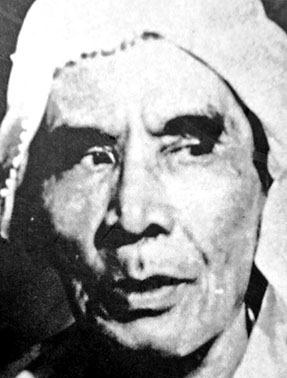Perubahan radikal itu terjadi setelah datang sepucuk surat dari orang tuanya. Mas’ud, si calon dokter Stovia itu harus pulang kembali ke Ploso. Sebuah perjalanan yang akan mengubah jalan hidupnya.
Berbilang bulan Mas’ud menjadi mahasiswa di Stovia. Hingga, suatu ketika, datang sepucuk
Menumpang kereta api, Mas’ud kembali ke Kediri. Dari Stasiun Kediri dia lantas menuju kediaman orang tuanya di Ploso, Mojo yang saat itu masih sangat jauh dari keramaian. Diliputi tanda tanya, Mas’ud masuk kediaman orang tuanya yang hingga kini masih berdiri kukuh di kompleks pondok induk Ponpes Al Falah, Ploso.
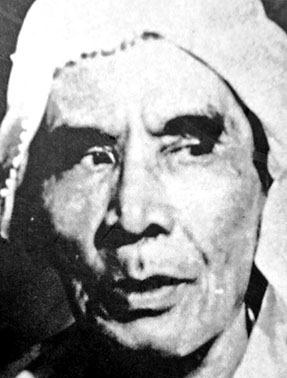
KH. Ahmad Djazuli Ustman
Akan tetapi, Utsman dan Ajeng Muntoqinah –ayah dan ibunya—tak segera memberi jawaban atas kegelisahan tersebut. Melainkan, justru segera mempersilakannya untuk beristirahat dan makan. Mereka seolah mengetahui benar bahwa fisik anaknya sudah banyak terkuras dalam perjalanan.
Baru, setelah beristirahat cukup, Mas’ud dipanggil, diajak berembuk dalam sebuah forum keluarga. Ternyata, di luar dugaan, Pak Naib Utsman yang dulu mendukungnya penuh masuk Fakultas Kedokteran di Stovia mendadak memintanya untuk mengurungkan niat.
Bukan soal kendala biaya. Akan tetapi, ini terkait dengan kedatangan Kiai Ma’ruf Kedunglo, Bandar beberapa saat setelah kepergian Mas’ud ke Batavia. Ulama kharismatik yang menjadi panutan Pak Naib Utsman itu berpesan agar Mas’ud diminta pulang saja untuk dimasukkan ke pesantren.
Utsman yang sebenarnya sangat berharap anaknya menjadi dokter itu pun tak mampu menolak. Dan, itulah yang kemudian dia sampaikan kepada Mas’ud. Butuh waktu lama untuk merenungkan dan menimbang-nimbang. Akan tetapi, Mas’ud yang sejak kecil memang dikenal sebagai pribadi penurut akhirnya menerima.
Dari situlah titik balik berawal. Usianya baru 16 tahun, usia yang tergolong cukup dewasa saat itu. Dari pendidikan modern Belanda yang ditempuhnya sejak dari Sekolah Cap Jago,
Dan, mulai saat itulah ‘petualangan keilmuan’-nya di dunia pesantren dimulai. Yang pertama dituju adalah Pesantren Gondanglegi, Prambon, Nganjuk asuhan KH Ahmad Sholeh yang terkenal ‘alim dalam bidang Ulumul Qur’an. Selain tajwid, di sana Mas’ud juga mendalami ilmu tata bahasa Arab (nahwu). Karena kecerdasannya, ilmu-ilmu itu bisa dikuasainya dalam waktu enam bulan.
Dari Gondanglegi, Mas’ud muda ganti bergeser ke
Di Pesantren Mojosari yang didirikan oleh KH Ali Imron sekitar abad 18 inilah Mas’ud banyak digembleng. Bukan hanya soal keilmuan agama, tapi juga tentang kehidupan dan kesederhanaan. Walau anak seorang ambtenaar, Mas’ud harus hidup prihatin. Bahkan, gara-gara tidak mampu membayar biaya mondok, dia harus rela tinggal di Langgar Pucung di luar kompleks pesantren.
Kesederhanaan sekaligus semangat pantang menyerah itulah yang kemudian menarik perhatian Kiai Zainuddin. Apalagi, Mas’ud tergolong sebagai santri yang cerdas –yang dari situ dia mendapat julukan Blawong (perkutut istimewa kesayangan Raja Brawijaya). Maka, dia pun diminta untuk tinggal di dalam kompleks pesantren tanpa harus membayar. Lalu, dalam perkembangannya, dia diambil menantu, dijodohkan dengan Badriyah, anak angkat Kiai Zainuddin.
Pascamenikah, perjalanan intelektual Mas’ud belum berhenti. Dia pergi ke Tanah Suci. Saat berhaji itulah, sang istri di Tanah Air meninggal karena sakit. Karena itu dia lantas bertekad untuk tidak pulang. Melainkan, melanjutkan ngaji-nya di Tanah Suci. Kali ini Mas’ud telah mengganti namanya menjadi Djazuli. Ditambah nama sang ayah di belakang menjadi Djazuli Utsman. Mengganti nama merupakan tradisi orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji pada masa itu.
Setelah sempat bekerja pada salah satu biro haji milik orang Makkah bersama Sahlan, sahabatnya sesama mukimin (orang yang menetap di Makkah) asal Pagu, Djazuli memutuskan untuk nyantri kepada Syaikh Al Alamah Al Aidrus di Jabal Hindi, Makkah. Setelah itu dia banyak diminta oleh para mukimin asal Indonesia untuk memberikan pengajian kepada mereka.
Semua tetap dijalani dengan laku prihatin. Bahkan, Djazuli harus tinggal di gudang karena tak mampu menyewa tempat tinggal yang layak. Dua tahun Djazuli menjalani hidup demikian di Makkah sebelum kemudian terjadi perebutan kekuasaan di Arab Saudi oleh kelompok Wahabi pimpinan Abdul Aziz As Su’ud. Semua orang asing yang tinggal di sana pun dipulangkan ke negaranya masing-masing, termasuk Djazuli.
Pulang dari Tanah Suci, nama Djazuli semakin moncer di Tanah Air. Niatnya untuk kembali menimba ilmu di Pesantren Tebuireng asuhan KH Hasyim Asy’ari malah berbalik. Dia diminta mengajar para santri di sana. Djazuli juga menjadi andalan Tebuireng untuk mewakili dalam forum-forum nasional.
Hal sama terjadi ketika Djazuli ingin nyantri ke Pesantren Tremas, Pacitan yang didirikan Syaikh Mahfudz At Tarmasy. Lagi-lagi di sana bukannya diterima sebagai santri, Djazuli justru diminta untuk mengajar para santri.
Dari Termas, Djazuli akhirnya kembali ke Ploso. Saat itu pertengahan 1924. Di sanalah, di pendapa kenaiban –tempat dia pernah dibesarkan, Djazuli merintis sebuah pesantren. Santri pertamanya hanya 12 orang dari sekitar Ploso.
Lalu, tepat pada 1 Januari 1925, dia mendaftarkan lembaga barunya itu dalam bentuk madrasah kepada pemerintah Hindia Belanda. Namanya Al Falah. Pusat kegiatannya di pendapa kenaiban –yang naibnya telah dijabat oleh Iskandar, kakaknya, sepeninggal almarhum Pak Naib Utsman. Pendapa yang kemudian berubah fungsi menjadi masjid itu masih berdiri tegak di tengah-tengah kompleks Ponpes Al Falah hingga kini. (*)


 Arif Hanafi
Arif Hanafi